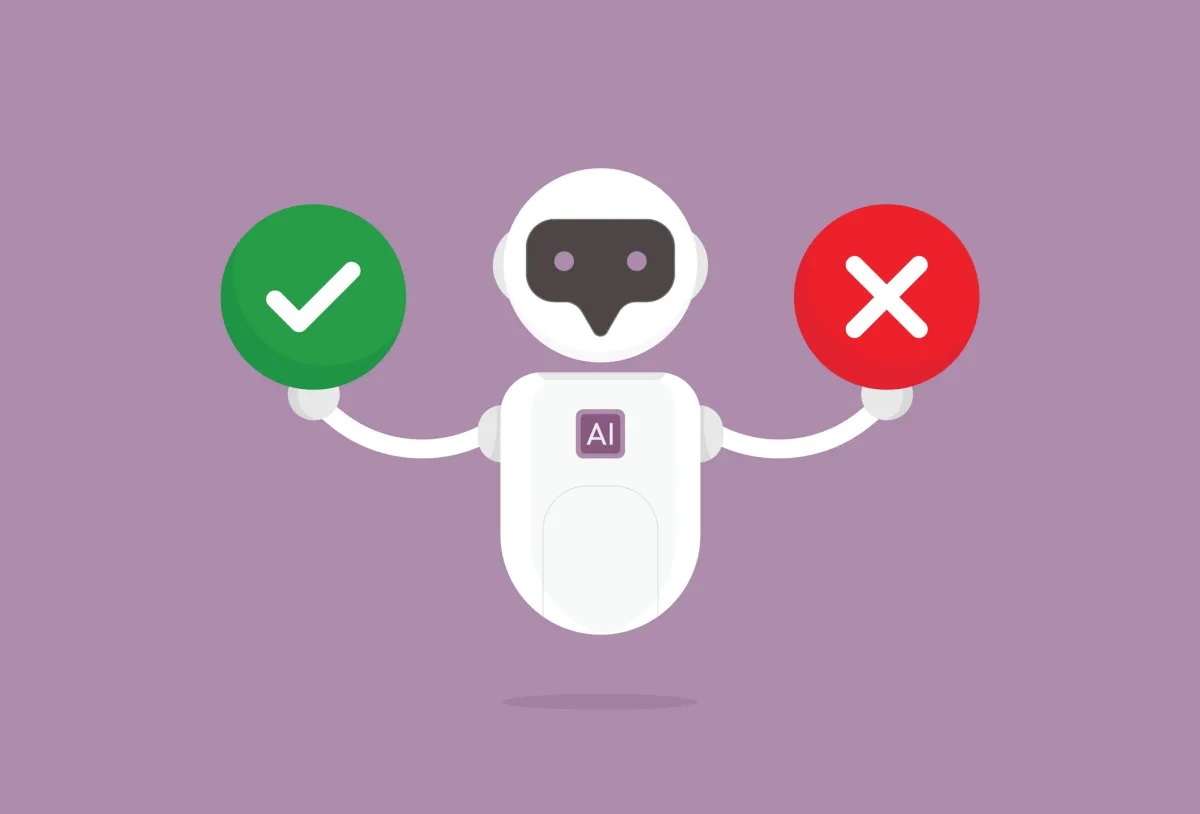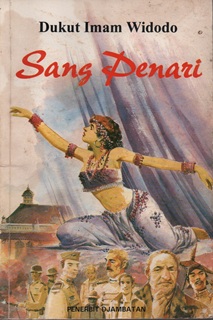Seorang ASN yang menulis agar tetap berpikir dan tetap merasa.
Dilema Kecil di Dunia ASN
4 jam lalu
Tulisan ini lahir dari kegelisahan kecil yang mungkin dirasakan banyak ASN tentang batas tipis antara kebersamaan dan kompromi dalam keseharian.
Tulisan ini tidak panjang. Saya menuliskannya agar pikiran saya sedikit lebih tenang malam ini. Kadang menulis membantu menata hal-hal yang sulit diucapkan, terutama bagi seorang yang bekerja di dunia birokrasi--dunia yang menuntut segala hal tampak masuk akal di atas kertas, meski kadang tak selalu demikian di dalamnya.
Beberapa hari lalu, suasana kantor berubah riuh. Obrolan di ruangan kami bukan lagi tentang laporan, melainkan tentang undangan pernikahan seorang rekan di luar kota. Hampir semua antusias. Jadwal mulai disesuaikan, surat tugas disiapkan, dan rencana keberangkatan disusun dengan rapi. Secara administratif, semuanya tampak sah. Tidak ada yang fiktif; bahkan hasil kegiatan pun nanti akan dibawa pulang sebagai bukti kerja.
Namun di balik semua kerapian itu, saya merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang di permukaan tampak benar, tetapi di dasarnya menyimpan pergeseran yang kita pilih untuk tidak melihatnya: fasilitas negara digunakan untuk kepentingan pribadi--bukan karena keserakahan individu, melainkan karena telah menjadi kebiasaan yang terdesain, dijalankan bersama, dan lama-lama terasa wajar.
Saya tahu, hal seperti ini tidak hanya terjadi pada satu acara pernikahan. Dalam berbagai kegiatan sosial lain--team building, syukuran, pertemuan daerah, atau sekadar kunjungan yang bertepatan dengan urusan pribadi--pola serupa sering muncul. Selalu ada cara membuatnya tampak formal, selalu ada laporan untuk menutupinya, dan selalu ada alasan yang terdengar masuk akal.
Di kantor, ada mungkin sepuluh orang lain yang belum menikah, dan sebagian besar berasal dari daerah. Jika tradisi seperti ini terus berulang, apakah kami akan melakukan hal yang sama di setiap pernikahan berikutnya? Jika iya, praktik itu akan makin kuat menjadi kebiasaan, bukan pengecualian. Jika tidak, bagaimana menjelaskan perbedaan perlakuan antara satu rekan dan rekan lain?
Saya tidak punya jawaban untuk itu. Saya hanya tahu bahwa sesuatu yang dibiarkan karena alasan baik sering kali tumbuh menjadi hal yang sulit dihentikan. Bukan karena semua orang ingin melanggar, tapi karena semua ingin diterima.
Saya juga tidak bisa menjelaskan alasan saya menolak ikut. Tidak ada cara yang sopan untuk berkata bahwa saya tidak nyaman dengan cara perjalanan ini disusun. Rekan yang menikah pasti akan menganggap saya tidak peduli, padahal justru karena saya peduli pada makna yang lebih besar dari sekadar hadir di pesta. Tapi saya tahu, dari sudut pandangnya, rasa terima kasihnya kepada rekan-rekan lain yang datang jauh lebih manusiawi daripada kegelisahan saya malam ini.
Mungkin beginilah dilema kecil yang sering muncul di dunia ASN--di antara rasa ingin menjaga kebersamaan dan keharusan menjaga garis etik yang kadang tampak terlalu tipis untuk diperhatikan. Saya tidak tahu apakah keputusan saya benar, tapi saya ingin tetap punya ruang untuk bertanya, setidaknya kepada diri sendiri.
Semua orang melakukannya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang dirugikan. Tapi mungkin di situlah persoalannya: kita mulai menilai benar dan salah hanya dari ada-tidaknya kerugian, bukan dari apakah sesuatu masih berada di tempat yang seharusnya. Hal yang menurut saya lebih menakutkan--karena ia menggerogoti dari dalam, dengan diam.
Malam itu saya memikirkan lebih jauh. Bahwa fenomena semacam ini, sesungguhnya, tidak hanya milik birokrasi. Di sektor swasta pun tidak luput dari hal serupa--perjalanan dinas yang diselipi agenda pribadi, rapat yang bergeser menjadi liburan. Bedanya, di sana pemilik sumber daya jelas: seseorang, keluarga, atau korporasi yang menanggung sendiri risikonya. Sedangkan dalam birokrasi, pemilik sumber daya itu tidak punya wajah. Ia bernama rakyat--terlalu luas, terlalu jauh, dan terlalu abstrak untuk benar-benar dirasakan.
Mungkin di situlah akar dari kelonggarannya: ketika amanah tidak lagi dirasakan sebagai titipan yang harus dijaga, melainkan sebagai milik bersama yang bisa digunakan sesuka pemegangnya. Padahal sumber daya negara bukan harta tanpa tuan; ia hanyalah titipan yang dipegang sementara, dengan tanggung jawab yang seharusnya lebih berat daripada kepemilikan pribadi.
Namun sistem sering kali mengajarkan hal sebaliknya. Selama surat tugas lengkap, laporan dibuat, dan tidak ada angka yang menimbulkan kerugian, semuanya dianggap beres. Padahal di balik legalitas itu, sesungguhnya ada bentuk penyalahgunaan yang dilembutkan, diulang, dan akhirnya diterima sebagai kebiasaan.
Dan di titik inilah yang paling sulit: ketika sesuatu yang salah tidak lagi menimbulkan rasa bersalah. Bukan karena orang tidak tahu, tetapi karena semua melakukannya bersama-sama--dengan senyum, rasa terima kasih, dan niat baik. Kita hidup di antara tekanan untuk kompak dan ketakutan dianggap kaku, hingga akhirnya rasa tidak enak lebih berat daripada rasa bersalah.
Mungkin beginilah cara nilai-nilai itu memudar. Tidak dengan pelanggaran besar, tapi dengan pembenaran kecil yang dilakukan perlahan, sistematis, dan kolektif.
Sendiri itu tidak enak...
Kadang saya bertanya untuk apa semua ini, kalau akhirnya hanya membuat jarak dengan orang lain. Tapi entah kenapa, saya belum bisa berpura-pura tidak peduli. Mungkin nanti akan terbiasa. Mungkin juga tidak.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Dilema Kecil di Dunia ASN
4 jam lalu
Yang Diam-diam (Harus) Kita Maklumi: Soal Ordal, Orang Lama dan Orang Dekat
Minggu, 11 Mei 2025 14:52 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan





 99
99 0
0